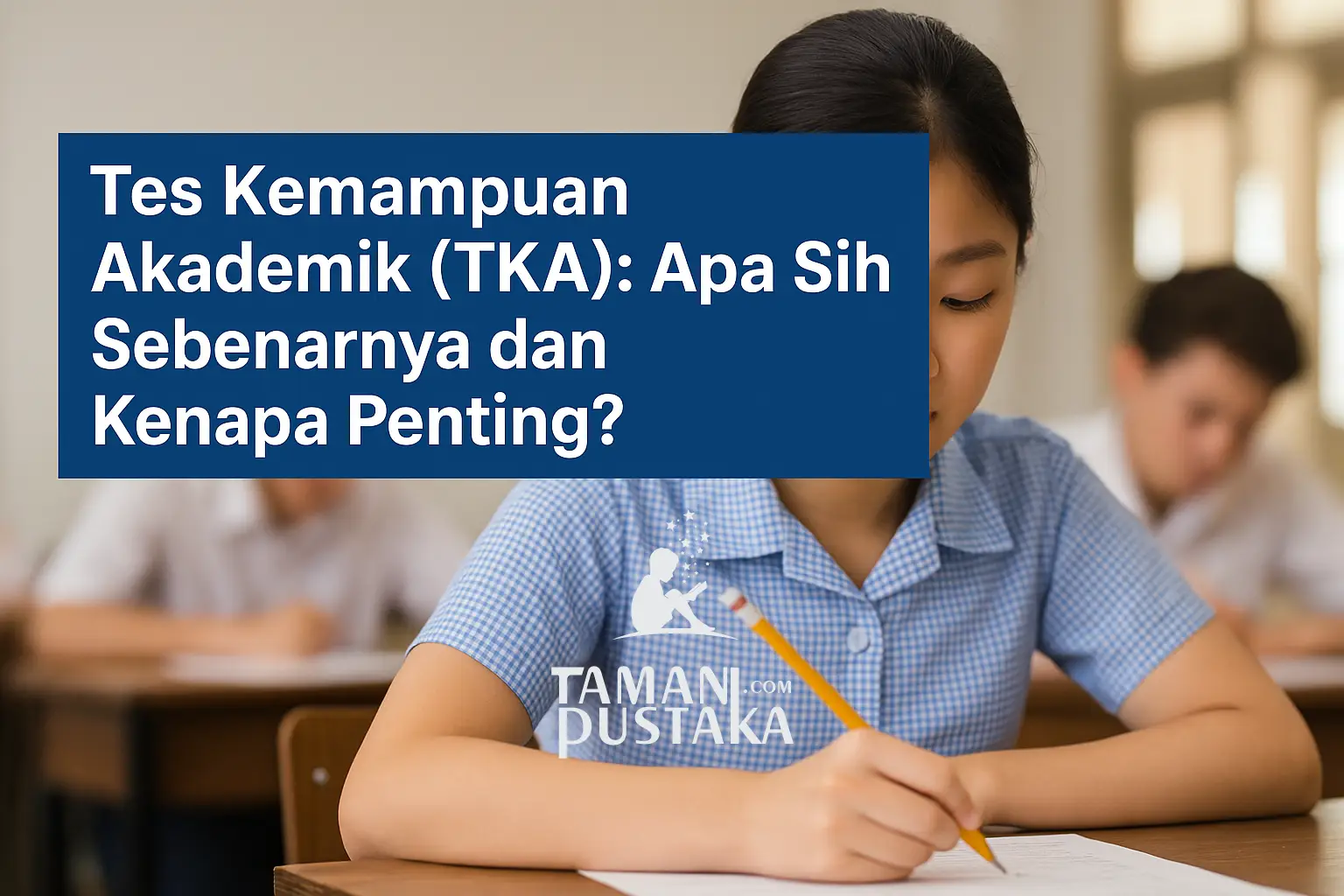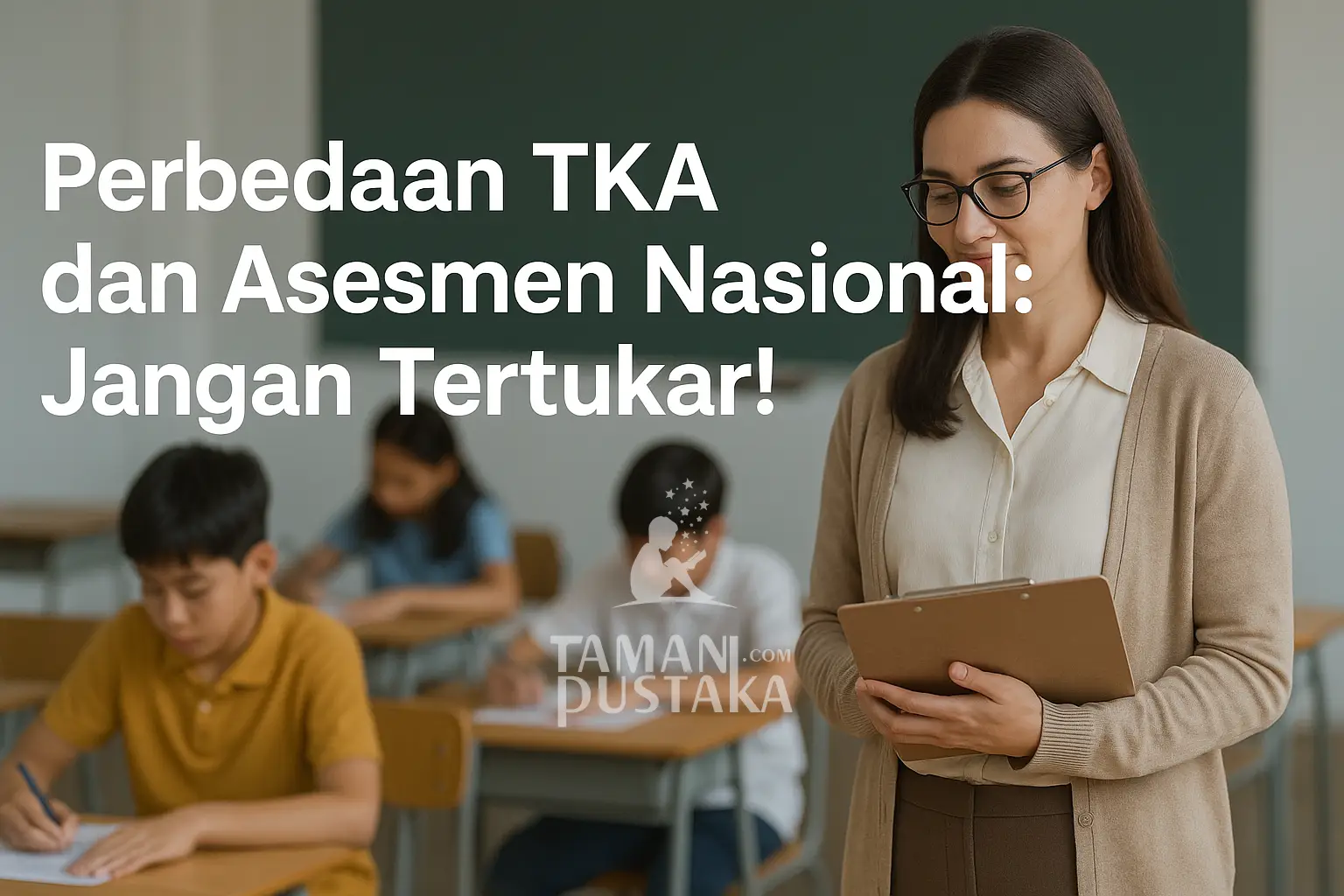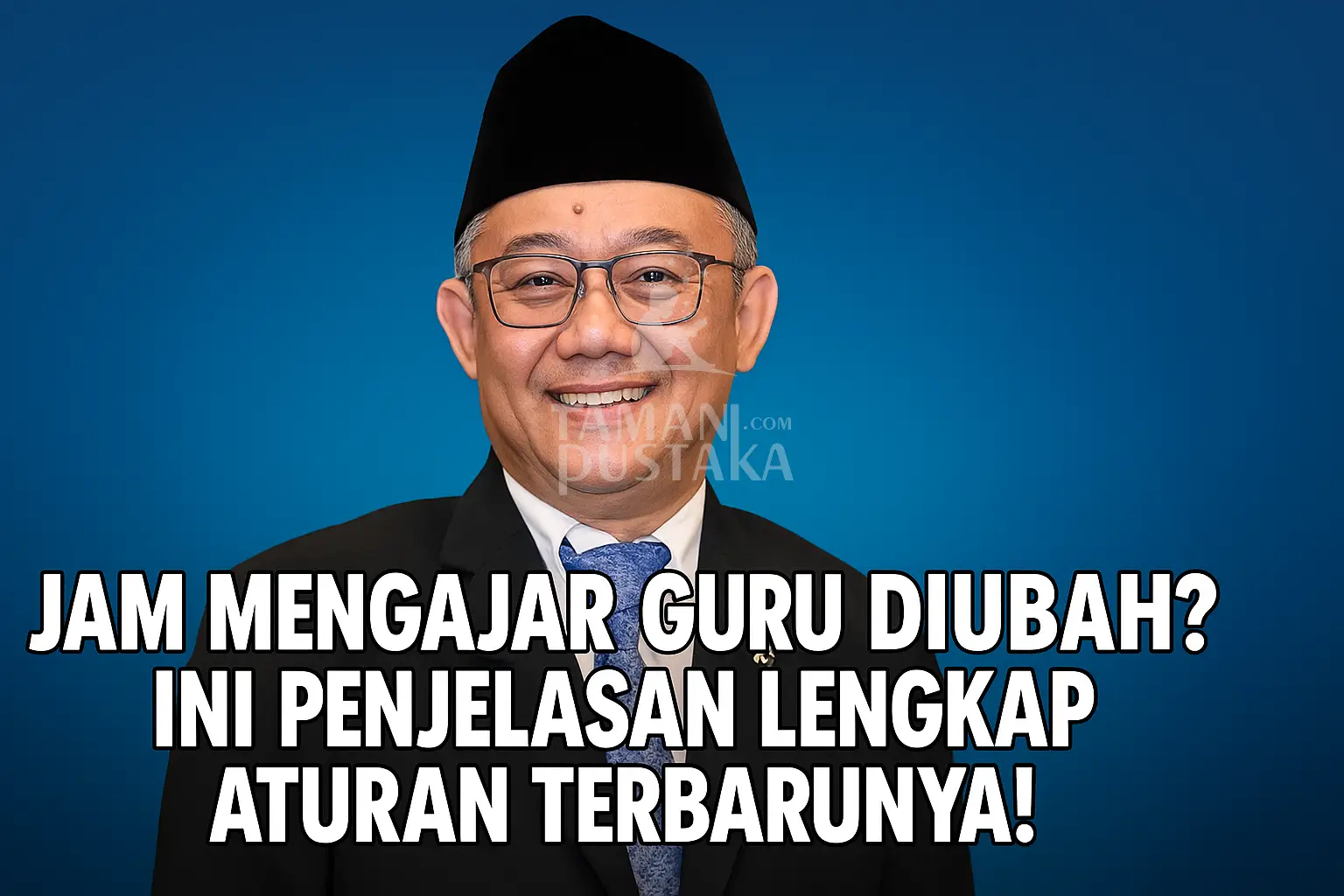BERITA PENDIDIKAN
Krisis Pendidikan Indonesia: Ketika Negara Abai, Murid Jadi Korban
24 - Juni - 2025 59 Share :Krisis pendidikan Indonesia: rendahnya kemampuan siswa, lemahnya kompetensi guru, dan abainya pemerintah dalam membenahi sistem.

Pendidikan adalah fondasi peradaban. Namun di Indonesia, fondasi itu mulai retak dari dalam. Di balik euforia kurikulum baru dan jargon transformasi digital, tersembunyi kenyataan pahit: kemampuan siswa merosot tajam, guru banyak yang tidak kompeten, dan pemerintah seolah menutup mata. Artikel ini mengupas tuntas data mencengangkan seputar krisis pendidikan nasional dan menyodorkan kritik tajam terhadap pengelola kebijakan.
Angka-angka yang Mengguncang Nurani
Kalau kamu pikir nilai rapor jelek itu cuma masalah pribadi, coba deh lihat data ini. 90% siswa SMA di Indonesia nggak bisa ngerjain soal matematika kelas 5 SD. Bukan karena lupa rumus segitiga atau salah hitung pecahan, tapi karena memang *nggak ngerti konsep dasarnya*. Lebih parah lagi, 30% siswa SMA bahkan masih kesulitan dengan materi selevel kelas 2 SD. Waduh... kalau begini terus, bukan "generasi emas" yang kita cetak, tapi "generasi lemas".
Mari kita bayangkan bareng: anak-anak kita terus naik kelas, lulus ujian, bahkan dapat ijazah. Tapi saat diminta ngitung 7 x 8, langsung garuk-garuk kepala sambil nyari kalkulator. Ini bukan salah mereka sepenuhnya. Kita harus jujur bahwa sistem pendidikan kita banyak bolongnya. Anak naik kelas bukan karena layak, tapi karena kasihan. Ya ampun, belajar kok pakai belas kasihan?
Belum cukup sampai situ, ada lagi yang lebih mengkhawatirkan: 55% siswa Indonesia nggak bisa membaca dan memahami teks dengan baik. Jadi jangan heran kalau banyak anak yang waktu ujian bilang, "Pak, ini soal maksudnya apa ya?" — karena mereka memang nggak ngerti isi bacaannya. Ini bukan hanya tentang bisa membaca kata per kata, tapi bisa menangkap makna, menyimpulkan, dan berpikir kritis dari apa yang dibaca. Nah, kemampuan itu yang sekarang sedang langka kayak warung nasi padang di luar negeri.
Dari sudut pandang kami sebagai pengamat dan pelaku pendidikan, ini adalah sinyal darurat. Saya sudah meliput pendidikan di berbagai daerah, dari sekolah unggulan di kota sampai ruang kelas berlantaikan tanah di pedalaman. Masalahnya sama: akses boleh membaik, tapi kualitas masih tertinggal. Program digitalisasi dan kurikulum baru terus bergulir, tapi fondasi dasarnya belum kuat. Ibarat rumah bagus tapi pondasinya keropos—ya bisa roboh kapan aja.
Jadi, ketika angka-angka ini keluar, seharusnya bukan sekadar jadi berita lalu lewat. Tapi jadi tamparan yang bikin kita sadar: ada yang salah besar. Kita nggak bisa lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Anak-anak kita berhak dapat pendidikan yang beneran mengajarkan, bukan cuma sekadar "numpang lewat" di sistem sekolah. Yuk, kita mulai peduli. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa?
Kompetensi Guru yang Memprihatinkan
Mari kita hadapi kenyataan yang agak pahit dan bikin cenat-cenut: sekitar 80% guru di Indonesia tidak lulus Ujian Kompetensi Guru (UKG) antara tahun 2012 hingga 2015. Bukan 8 persen, bukan 18 persen, tapi 80! Itu artinya, dari 10 guru, hanya 2 yang secara kompetensi bisa dikatakan layak mengajar menurut standar pemerintah sendiri. Sisanya? Ya, bisa dibilang masih perlu banyak belajar.
Nah, kalau guru aja masih struggling ngerjain soal-soal standar UKG, gimana dengan muridnya? Gimana bisa kita berharap ada murid jago matematika atau paham IPA, kalau gurunya sendiri bingung mana rumus dan mana cerita? Kita jadi seperti minta anak buah mendaki gunung, tapi pemandunya nggak tau arah utara.
Saya sendiri pernah mewawancarai guru-guru di beberapa daerah terpencil. Banyak di antara mereka sebenarnya punya semangat luar biasa. Tapi sayangnya, mereka mengajar dengan fasilitas minim, pelatihan jarang, dan literatur terbatas. Bahkan ada guru yang sudah puluhan tahun mengajar tapi belum pernah ikut pelatihan apa pun sejak jadi PNS. Ibaratnya, skill-nya mandek di tahun mereka lulus kuliah. Zaman udah pakai Google Lens, mereka masih pakai fotokopian dari 2003.
Di sisi lain, tak sedikit pula guru yang sebetulnya malas berkembang. Ada yang menganggap pelatihan itu cuma formalitas, asal tanda tangan dan dapat sertifikat. Padahal seharusnya pelatihan jadi momen buat upgrade ilmu dan metode. Ini jadi catatan penting juga buat pemerintah: evaluasi kualitas pelatihan guru, bukan cuma kuantitasnya. Pelatihan yang bikin ngantuk dan terlalu teoritis ya nggak akan ngaruh.
Guru itu pelita bagi murid-muridnya. Tapi kalau pelitanya redup atau bahkan nggak dinyalakan, ya kelas jadi gelap. Jangan sampai kita punya generasi guru yang pasif, karena dampaknya langsung terasa ke murid. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, ya harus mulai dari gurunya. Bukan sekadar kasih honor atau tunjangan, tapi kasih mereka tools, pelatihan bermutu, dan budaya belajar berkelanjutan. Karena guru yang hebat bukan yang tahu segalanya, tapi yang mau terus belajar tanpa henti.
Otonomi Daerah: Kebijakan Tanpa Tanggung Jawab
Waktu otonomi daerah digulirkan, banyak yang berharap besar: "Wah, ini bakal bikin pendidikan makin dekat dengan rakyat!" Tapi kenyataannya, 90% kabupaten/kota di Indonesia tidak punya program nyata untuk meningkatkan kualitas guru SD dan SMP. Lho? Bukannya sudah diberi wewenang? Kok malah ditinggal tidur siang?
Ibarat dikasih kunci rumah tapi malah ditinggal kosong, begitu kira-kira yang terjadi di banyak daerah. Guru butuh pelatihan? “Nanti kita usulkan.” Sekolah butuh pendampingan? “Belum ada anggaran.” Anak-anak makin tertinggal? “Itu urusan guru.” Nah, kalau semuanya dilempar ke sekolah, lalu fungsi dinas pendidikan daerah itu apa dong? Cuma buat urus seragam upacara?
Dari pengalaman saya turun ke lapangan, banyak sekolah di pelosok yang mengandalkan inisiatif kepala sekolah atau komunitas guru sendiri untuk belajar. Ada yang sampai patungan beli proyektor, bikin pelatihan mandiri, atau nebeng sinyal Wi-Fi dari kelurahan. Sementara dinasnya? Sibuk rapat entah bahas apa, mungkin bahas lomba gaplek antar kecamatan.
Ini bukan cuma soal dana. Ini soal komitmen. Banyak daerah yang sebenarnya mampu secara anggaran, tapi tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Yang dikejar justru proyek fisik: bangun taman kota, air mancur warna-warni, gapura setinggi tugu monas. Tapi pendidikan? Dibiarkan mengalir sendiri kayak air got waktu musim hujan.
Kita harus jujur dan tegas: otonomi tanpa tanggung jawab adalah bencana. Jika pemerintah daerah tidak mampu atau tidak mau mengurus pendidikan, maka pemerintah pusat tidak bisa terus diam. Harus ada mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, dan sanksi bagi pemda yang abai. Karena kalau kita terus membiarkan ini berjalan tanpa koreksi, maka yang jadi korban adalah anak-anak kita—generasi masa depan yang tumbuh tanpa pegangan, tanpa arah.
Pendidikan itu bukan sekadar angka di RPJMD atau bahan pidato saat Musrenbang. Pendidikan adalah soal masa depan, dan masa depan tidak bisa dikelola dengan asal-asalan. Yuk, kita dorong kepala daerah untuk tidak cuma sibuk kampanye, tapi juga turun tangan memperbaiki mutu sekolah di wilayahnya. Karena pendidikan yang kuat dimulai dari keberanian untuk peduli.
Kritik Keras untuk Pemerintah
Kalau boleh jujur, pemerintah pusat ini kadang lebih jago main kata daripada main data. Ketika ditanya kenapa kualitas pendidikan memburuk, jawabannya simpel: “Itu kewenangan daerah.” Lho, enak banget ya? Giliran bikin aturan, semangatnya luar biasa. Tapi giliran tanggung jawab, langsung lempar ke kabupaten/kota. Padahal, sistem pendidikan nasional itu satu tubuh. Kalau kepala cuma bisa nunjuk, tapi tangan dan kakinya kepleset terus, ya jalannya pincang, bro!
Pemerintah daerah juga bukan tanpa salah. Banyak yang lebih suka bangun jalan dan gedung ketimbang bangun karakter dan otak. Yang penting bisa difoto dan diresmikan, ada plakatnya, ada pita untuk digunting. Tapi soal pelatihan guru, perbaikan kurikulum lokal, atau peningkatan literasi — itu mah dianggap kerjaan sampingan. Akhirnya, pembangunan manusia kalah pamor sama proyek taman selfie.
Saya pernah meliput langsung proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di salah satu kabupaten. Tahu apa yang paling heboh dibahas? Tempat wisata baru dan stadion mini. Sementara pengadaan buku pelajaran dan pelatihan guru cuma diselipkan lima menit di akhir rapat. Padahal, stadion bisa roboh kalau isinya generasi yang nggak ngerti fair play, apalagi matematika dasar.
Di sinilah letak masalah utamanya: tidak ada komitmen politik yang kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas nyata. Semua orang bilang “pendidikan penting,” tapi saat bagi-bagi anggaran, pendidikan dapat sisa-sisa. Kurikulum baru digembar-gemborkan, padahal guru belum siap, fasilitas kurang, dan evaluasi minim. Ujung-ujungnya? Murid jadi kelinci percobaan terus.
Pemerintah pusat seharusnya tidak hanya membuat aturan, tapi juga turun tangan memastikan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Jangan hanya muncul saat peluncuran kurikulum atau meresmikan gedung sekolah baru. Turunlah ke kelas-kelas kecil di daerah terpencil, dengarkan guru yang mengajar pakai papan tulis usang, dan lihat murid-murid yang belajar tanpa buku. Di situlah wajah asli pendidikan Indonesia.
Jadi, kritik ini bukan soal menyalahkan. Tapi soal mengingatkan. Bahwa anak-anak kita butuh lebih dari sekadar kurikulum dan slogan. Mereka butuh sistem yang peduli, pemimpin yang turun tangan, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan. Karena kalau terus begini, jangan salahkan murid kalau mereka lebih paham TikTok daripada teks bacaan. Siapa suruh sistemnya penuh drama?
Rekomendasi Solusi Nyata
Setelah panjang lebar mengupas masalahnya, masa kita cuma bisa ngedumel? Nah, ini dia bagian pentingnya: solusi nyata. Bukan sekadar jargon seminar atau janji kampanye, tapi langkah-langkah yang benar-benar bisa dilakukan — asalkan niatnya serius, bukan asal “yang penting ada program”.
Pertama-tama, evaluasi dan pelatihan ulang guru itu wajib hukumnya. Tapi jangan cuma formalitas, ya. Harus benar-benar terukur, dibimbing oleh mentor yang paham, bukan hanya “bapak-bapak dari pusat” yang datang, ngomong PowerPoint 2 jam, lalu pulang. Guru itu butuh dibekali metode baru, teknologi pendidikan, dan strategi mengajar yang kontekstual. Kalau bisa, sekalian difasilitasi komunitas belajar antar guru. Biar nggak ngerasa berjuang sendirian kayak sinetron sore.
Kedua, pemerintah pusat jangan cuma ngatur, tapi juga turun tangan. Kalau ada daerah yang gagal total dalam urusan pendidikan, ya jangan dibiarkan. Harus ada intervensi berbasis data. Bisa lewat program khusus, pengawasan intensif, atau bahkan insentif bagi daerah yang performa pendidikannya meningkat. Karena membiarkan daerah gagal adalah sama dengan membiarkan anak-anak di sana kehilangan masa depan.
Ketiga, program literasi dan numerasi harus dijadikan gerakan nasional. Nggak usah muluk-muluk dulu ke coding atau AI, kalau anak-anak masih bingung baca paragraf atau hitung 8 x 7. Mari kita mulai dari dasar yang kuat. Kalau fondasi oke, yang lain bisa nyusul.
Keempat, anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Jangan sampai lebih banyak dana habis buat spanduk, makan siang rapat, atau studi banding ke luar negeri yang isinya selfie. Fokus ke fasilitas belajar, pelatihan guru, dan pembelajaran yang berkualitas. Ingat, membangun manusia lebih penting daripada membangun monumen.
Terakhir tapi nggak kalah penting: libatkan publik. Orang tua, komunitas, LSM, bahkan siswa itu sendiri bisa jadi mitra. Buka ruang partisipasi. Kasih ruang untuk kritik, saran, dan kontrol sosial. Karena pendidikan itu bukan milik pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama.
Intinya, kita nggak butuh solusi rumit atau aplikasi canggih dulu. Kita butuh kemauan tulus untuk memperbaiki. Karena kalau sekarang kita nggak bergerak, bisa-bisa nanti generasi penerus lebih paham skin Mobile Legends daripada sila Pancasila.

Aristo Bharata
Founder tamanpustaka.com & guru di UPTD SPF SDN Sekarputih 1 Kecamatan Tegalampel Bondowoso